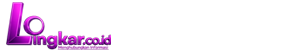Penulis : Abdul Muarif Korois S.H
Lingkar.co id—Wacana mengenai pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang kembali mencuat menjelang tahun 2026, bagian dari sebuah diskursus yang menuntut ketajaman analisis melampaui perdebatan efisiensi anggaran atau stabilitas politik semu.
Sebagai seorang penstudi yang mencoba memahami dinamika ini dari keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, penulis melihat bahwa polemik ini tidak cukup jika hanya dibedah menggunakan pisau analisis konstitusional normatif semata. Terdapat dimensi lain yang jauh lebih mendasar dan berdampak panjang, yakni dimensi institusional yang berkaitan erat dengan struktur insentif, distribusi kekuasaan, dan potensi penyimpangan. Dalam konteks inilah, kerangka teoritis Robert Klitgaard yang penulis tawarkan menjadi sangat relevan untuk kita kontemplasikan bersama.
Penulis tidak bermaksud menggarami air di laut, tapi kita semua tahu dan bahkan paham; bahwa problem ini adalah persoalan yang menyentuh jantung integritas demokrasi kita. Oleh karena itu, izinkan saya menguraikan pandangan ini dengan berpijak pada formula klasik Klitgaard mengenai korupsi politik; bukan untuk menggurui, melainkan untuk memetakan risiko yang mungkin luput dari pandangan kita.
Baca Juga : Peta Pemikiran Hans Nawiasky
Dalam perspektif Robert Klitgaard, korupsi dan penyimpangan kekuasaan bukanlah sekadar persoalan moralitas individu yang buruk, melainkan hasil dari sebuah sistem yang memfasilitasi perilaku tersebut.
Klitgaard merumuskan sebuah persamaan yang kini menjadi aksioma dalam studi kebijakan publik dan antikorupsi, yaitu: C = M + D – A, (C) adalah Corruption (Korupsi),(M) adalah Monopoly (Monopoli), (D) adalah Discretion (Diskresi), dan (A) adalah Accountability (Akuntabilitas).
Jika kita menarik formula ini ke dalam gelanggang Pilkada via DPRD, kita akan menemukan bahwa usulan perubahan mekanisme Pilkada lewat DPRD ini secara teoritis justru meningkatkan variabel Monopoli dan Diskresi, sembari secara drastis menurunkan variabel Akuntabilitas. Ini adalah sebuah resep institusional yang secara matematis dan sosiologis membuka lebar pintu bagi terjadinya korupsi politik, patronase, dan transnasionalisme yang lebih masif di balik pintu-pintu tertutup gedung parlemen daerah.
Mari kita bedah variabel pertama, yaitu Monopoli (M). Dalam sistem pemilihan langsung, “pasar” suara tersebar kepada ratusan ribu bahkan jutaan pemilih. Tidak ada entitas tunggal yang memonopoli hak untuk menentukan siapa yang menjadi kepala daerah; kedaulatan itu terdistribusi.
Namun, ketika pemilihan dikembalikan ke tangan DPRD, kita sedang menciptakan sebuah struktur monopoli kekuasaan yang absolut. DPRD bertransformasi menjadi gatekeeper tunggal atau pemegang hak eksklusif dalam menunjuk eksekutif daerah.
Dalam logika ekonomi-politik yang dijelaskan Klitgaard, monopoli atas sebuah “produk” (dalam hal ini, kursi kepala daerah) akan meningkatkan posisi tawar pemegang monopoli tersebut secara signifikan. Para anggota dewan, sebagai pemegang hak suara yang jumlahnya sangat terbatas (hanya puluhan orang), memiliki kekuatan pemaksa yang luar biasa terhadap para kandidat.
Alhasil, proses kontestasi bukan lagi tentang siapa yang paling mampu memenangkan hati rakyat melalui program kerja, melainkan siapa yang mampu memberikan penawaran terbaik kepada pemegang monopoli suara tersebut. Inilah titik awal di mana kedaulatan rakyat tereduksi menjadi negosiasi elit.
Baca Juga : FMS Hadir Sebagai Solusi Bagi Mahasiswa Sula
Selanjutnya, kita beranjak ke variabel kedua yang tidak kalah krusialnya, yakni Diskresi (D). Diskresi dalam konteks ini merujuk pada keluasan kewenangan yang dimiliki oleh anggota DPRD untuk mengambil keputusan tanpa batasan yang ketat atau panduan yang objektif. Ketika pemilihan dilakukan oleh DPRD, setiap anggota dewan memiliki ruang diskresi yang sangat besar untuk memberikan suaranya kepada kandidat A atau kandidat B.
Pertanyaannya adalah, atas dasar apa diskresi itu digunakan? dalam ruang yang tertutup dan jauh dari jangkauan pengawasan publik langsung, diskresi ini sangat rentan disalahgunakan bukan untuk kepentingan konstituen, melainkan berdasarkan instruksi partai, pertukaran kepentingan (logrolling), atau bahkan insentif finansial pribadi.
Klitgaard mengingatkan kita bahwa semakin besar diskresi yang tidak diimbangi dengan standar etika atau prosedur yang transparan, semakin tinggi potensi terjadinya penyimpangan. Dalam Pilkada DPRD, diskresi anggota dewan menjadi komoditas yang sangat berharga, dan sejarah politik kita sebelum 2005 telah memberikan pelajaran pahit bagaimana “kreativitas” dalam menggunakan diskresi ini sering kali berujung pada praktik politik uang yang kita kenal sebagai serangan fajar di tingkat elit atau “mahar politik“.
Variabel ketiga, yang menjadi pengurang atau penyeimbang dalam rumus Klitgaard, adalah Akuntabilitas (A). Di sinilah letak kelemahan paling fatal dari sistem Pilkada lewat DPRD. Dalam pemilihan langsung, akuntabilitas bersifat vertikal dan langsung; jika seorang kepala daerah berkinerja buruk atau korup, rakyat memiliki mekanisme penghukuman langsung dengan tidak memilihnya kembali.
Tapi, dalam skema pemilihan oleh DPRD, rantai akuntabilitas ini terputus atau setidaknya menjadi sangat bias. Sebab kepala daerah terpilih tidak lagi merasa memiliki utang budi atau tanggung jawab langsung kepada rakyat, melainkan kepada oligarki partai dan anggota dewan yang memilihnya.
Akibatnya, akuntabilitas publik menjadi rendah karena masyarakat kehilangan akses untuk memantau, menilai, dan memberikan sanksi politik secara langsung. Hubungan yang terbentuk adalah hubungan patron-klien antara eksekutif dan legislatif, di mana pengawasan menjadi tumpul karena adanya kolusi kepentingan. Sebagaimana tesis Boven tentang akuntabilitas, pejabat harus dapat menjelaskan dan menjustifikasi perbuatannya di hadapan publik.
Namun, jika mandat kekuasaan didapat dari ruang tertutup DPRD, kepada siapakah justifikasi itu akan diberikan? Besar kemungkinan, pertanggungjawaban hanya akan menjadi ritual formalitas di antara elit semata.
Analisis ini membawa penulis pada sebuah sintesis yang mengkhawatirkan bahwa Pilkada via DPRD, jika dibaca melalui kacamata Klitgaard, adalah sebuah langkah mundur yang berbahaya bagi desain integritas publik kita.
Argumen para pendukung yang menyatakan bahwa sistem ini akan menghemat anggaran negara dan mengurangi konflik horizontal mungkin terdengar logis di permukaan. Namun, mereka melupakan biaya tersembunyi (hidden cost) yang jauh lebih besar, yaitu biaya korupsi struktural.
Sebagai penutup dari telaah sederhana ini, penulis ingin menegaskan kembali bahwa reformasi politik dan demokrasi lokal tidak boleh hanya terjebak pada nostalgia masa lalu atau pertimbangan teknis sesaat, kita harus melihat konsekuensi praktis dan institusional dari setiap kebijakan.
Karena dengan itu, membaca Pilkada lewat DPRD dengan perspektif Robert Klitgaard memberikan kita peringatan dini bahwa ketika kita memberikan monopoli kekuasaan kepada segelintir orang, memberikan mereka diskresi tanpa batas yang jelas, dan pada saat yang sama mencabut mekanisme akuntabilitas langsung rakyat, maka kita sesungguhnya sedang menggelar karpet merah bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Demikianlah pandangan yang dapat penulis sampaikan, semata-mata sebagai upaya urun rembuk dalam menjaga kualitas demokrasi kita agar tidak terperosok ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya.